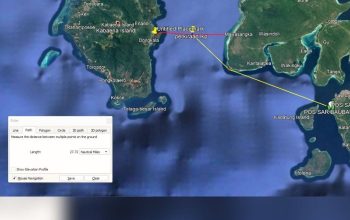SULTRABERITA.ID, KENDARI – Pandemi Covid-19 tidak hanya memberi dampak secara ekonomi, tapi juga psikologis. Dukungan keluarga, kerabat hingga lingkungan tempat tinggal pada para pasien Covid-19 menjadi imun booster kasat mata. Bukan stigma.
Masih kuat dalam ingatan Wa Ode Marni kejadian Jumat (22/5) malam, tepat dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
“Malam itu, saya sedang persiapkan bahan makanan untuk masakan lebaran lusa. Tiba-tiba, kami, satu keluarga, dijemput beberapa orang yang menggunakan pakaian astronot,” kata perempuan yang biasa dipanggil Marni itu.

Yang dimaksud perempuan berusia 33 tahun itu adalah personel tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Marni dan keluarga dijemput dari rumah kontrakan tempat mereka tinggal karena hasil swab test miliknya, yang dilakukan setelah proses melahirkan sekitar 10 hari sebelumnya, menunjukkan dia positif terpapar Covid-19.
Saat dijemput tim Gugus Tugas Covid-19, mereka hanya punya waktu 30 menit untuk berkemas. Marni sekeluarga serta bayi mungilnya yang masih merah harus meninggalkan semua barang miliknya di kontrakan. Mereka meninggalkan rumah hanya dengan baju yang melekat di badan.
Oleh tim Gugus Tugas Covid-19 mereka sekeluarga ditempatkan di sebuah rumah di wilayah pesisir Kota Bau-Bau. Dari informasi yang didapatnya, yang positif terpapar Covid-19 hanya dirinya. Hasil tes swab anggota keluarga yang lain negatif, teramsuk bayi yang baru dilahirkannya. Marni senang.

Tapi, kegembiraannya hanya sementara. Informasi keberadaan dirinya sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang berstatus positif Covid-19, tersebar ke lingkungan sekitar. Warga setempat menolak lingkungannya menjadi lokasi karantina meski penempatan Marni sekeluarga di lokasi ini adalah keputusan pemerintah.
Marni sempat menolak pindah dari rumah isolasi. Dia tidak mau berpisah dengan bayinya. Terutama karena dia ingin memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayinya.
“Saya tidak mau pisah dengannya. Tapi, kata petugas, warga sudah panas dan menolak kehadiran kami. Saya tidak punya pilihan. Saya keluar dari rumah itu jam 12 malam,” kata Marni.
Tim Gugus Tugas memindahkan Marni ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palagimata untuk melanjutkan isolasi. Hampir tiga pekan dia berada di ruang isolasi. Sendirian, terpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Termasuk bayi mungil yang baru dilahirkannya.
Mengingat hal itu, Marni sedih bercampur marah. Bukan karena dia terpapar Covid-19, melainkan karena dia harus berpisah dengan bayinya. Perpisahan itu membuatnya tidak bisa maksimal memberikan ASI eksklusif bagi bayinya.
Selama Marni diisolasi, sang suami merawat bayi dan anak-anak mereka di sebuah rumah kontrakan yang lokasinya tidak dipublikasikan ke warga. Hal itu untuk mencegah terulangnya kembali penolakan oleh warga, meski sang suami dan anak-anaknya negatif Covid-19.
Ketiadaan donor ASI membuat sang bayi mendapatkan susu formula yang dikirimkan oleh tim Relawan Tenaga Kesehatan (Nakes) Independen di kota itu. Sementara, untuk kebutuhan hidup lainnya disalurkan melalui tim Gugus Tugas Covid-19.
Kini, meski Marni dinyatakan sudah sehat dan negatif Covid-19, penderitaanya belum berakhir. Kabar sang istri yang dinyatakan sebagai pasien positif Covid-19, berdampak langsung terhadap penghasilan sang suami. Suami yang harus menjaga dan merawat anak-anak mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali. Satu-satunya sepeda motor yang menjadi sumber penghasilan mereka, disita karena mereka tidak mampu membayar angsuran.
Tidak hanya itu, mereka tidak dapat kembali ke rumah kontrakan bulanan sebelumnya karena telah ditempati-berpindah tangan ke pengontrak lain. Bahkan sang suami hanya datang mengambil barang-barang milik mereka.
Beruntung sang suami akhirnya dipekerjakan sebagai penjaga kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bau-Bau dengan gaji Rp 500 ribu per bulan. Bekerja sebagai penjaga kantor membuat Marni dan keluarga bisa tinggal di sebuah bangunan yang tidak terpakai di lingkungan BPBD.
Kesulitan demi kesulitan yang menimpanya, tidak membuatnya mendapat dukungan dari keluarganya. Bahkan kerabat dekat yang diharapkan bisa memberikan dukungan, setidaknya dukungan psikologis, membalikkan tubuh dan wajah mereka. Tidak hanya saat menjalani masa karantina, ketika sudah dinyatakan sehat pun, tak ada yang menyapa Marni dan keluarganya.
“Saya berpikir, kalau saya meninggal, siapa yang akan melayat? Keluarga sendiri tidak mau bersilaturahmi,” ujarnya.
Perang Informasi vs Stigma dari Lingkungan
Perlakuan yang diterima Marni sekeluarga adalah bagian kecil dari proses panjang penyembuhan, baik fisik maupun psikologis, pasien Covid-19. Informasi yang tidak akurat, menyesatkan, dan tersebar luas dari satu pintu ke pintu lain, melalui percakapan langsung ataupun melalui media sosial, berujung pada stigma.
Sosialisasi apa, bagaimana dan cara serta risiko tertular Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah kalah cepat dengan isu, kabar burung tentang warga yang positif terpapar Covid-19. Kabar burung melesat lebih cepat dari gerak dan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19. Pada akhirnya menghambat pemeriksaan spesimen dan pelacakan riwayat kontak.
La Ode Muh Ishaq, koordinator Tim Relawan Tenaga Kesehatan Independen menilai pemerintah Kota Bau-Bau sangat lambat bergerak. Tidak hanya dalam penanganan pasien Covid-19 tapi juga dalam sosialisasinya.
Berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber yang berkontak langsung dengan penanganan pasien Covid-19 di lapangan, tim Relawan Nakes Independen mendapati beberapa pasien Covid-19 dan keluarganya di sejumlah kelurahan mendapat perlakuan yang diskriminatif dari warga tempat mereka tinggal. Perlakuan yang diterima mereka mulai dari cibiran hingga tindakan menutup hidung ketika warga melewati rumah-rumah mereka. Bahkan, ketika ada kerabat warga yang positif Covid-19 hendak membeli obat anti-malaria, yang semula digadang-gadang ampuh dan bisa menyembuhkan penyakit ini, warga berkumpul dan menghalanginya.
Kondisi seperti ini, menurut Ishaq, terjadi karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi yang masif kepada warganya, tidak melakukan upaya edukasi pada masyarakat untuk memahami dan menerima warga yang tengah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Dengan hanya mengandalkan kendaraan operasional roda empat yang dilengkapi dengan pengeras suara, menurut Ishak, sosialisasi tidak akan berjalan maksimal.
Pandangan serupa dikatakan Mh Firdaus, anggota Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan. Menurutnya, tindakan penghalang-halangan keluarga pasien mencari obat, bukan bentuk dukungan moril yang baik dan bisa mempercepat penyembuhan pasien. Kondisi seperti itu mengakibatkan trauma psikologis yang mungkin akan lama untuk diobati. “Masyarakat perlu diedukasi,” kata dia.
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Baubau pun tidak sigap bergerak ketika mengetahui ada pasien Covid-19 yang distigma oleh warga di sekitar tempat tinggalnya. Samsuri, Sekretaris DPP2A, mengatakan, hanya bisa bertindak bila korban atau perwakilan korban melapor. Mereka tidak bisa jemput bola.
“Tidak ada pelaporan, tidak ada tindakan,” kata dia.
Bahkan, dia mengatakan, seharusnya hal itu menjadi tanggung jawab Satgas Gugus Covid-19. “Ketika ada kejadian seperti itu, harusnya mereka (Satgas Gugus Covid-19) saling konfirmasi untuk melakukan mediasi atau berdampingan” kata Samsuri.
Efek Psikologis dan Perbaikan Informasi
Marni dan keluarga tidak sendiri. Hal yang terjadi pada Marni dan keluarganya diyakini juga terjadi pada ratusan atau bahkan puluhan ribu pasien Covid-19 di Indonesia. Tidak hanya warga yang positif, tapi yang masih menyandang status orang dalam pengawasan atau suspek pun sudah dilabeli warga dengan sesuatu yang buruk.
Kondisi ini sejalan dengan temuan tim Lapor Covid-19 dan Kelompok Peminatan Intervensi Sosial Fakultas Psikologi Univeritas Indonesia. Dicky Pelupessy, Psikolog Sosial UI yang menjadi juru bicara penelitian dalam webinar survey Melawan Stigma Covid-19, Kamis (27/9) mengungkapkan, sebagian besar responden, dari 181 responden valid yang merupakan penyintas Covid-19, menjadi buah bibir atau digosipkan oleh warga sekitar tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, mereka juga dikucilkan, mendapat julukan sebagai penyebar penyakit mematikan hingga mengalami perundungan di media sosial. Yang lebih menyakitkan, para penyintas ini juga sempat mengalami penolakan mengakses fasilitas umum ketika sudah pulih.
Stigmatisasi tidak hanya menimpa warga yang dinyatakan positif terpapar Covid-19. Sama seperti perlakuan yang diterima anggota keluarga yang positif Covid-19, anggota keluarga yang tinggal bersama juga mendapatkan stigma dari warga: mulai dari menjadi buah bibir, dikucilkan, mendapat julukan negatif hingga penolakan untuk mengakses fasilitas umum atau fasilitas kesehatan.
Dicky mengatakan, dua penyebab utama munculnya tindakan-tindakan seperti itu adalah karena masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup atau mendapat informasi yang salah mengenai pasien Covid-19 di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, kekhawatiran tertular memicu mereka melakukan tindakan stigmatisasi terhadap pasien Covid-19 dan keluarganya.
Stigma memunculkan problem psikologis, terutama bagi penyintas, terutama depresi tinggi dan gangguan penyesuaian. Selain itu, para penyintas juga mengalami gangguan kecemasan meski sudah dinyatakan sembuh.
Studi singkat ini juga menerangkan bahwa minimnya informasi yang akurat sebagai penyebab utama harus dilawan dengan membanjiri warga dengan informasi yang akurat dan benar. “Kemunculan rumor, hoaks, gosip dan sejenisnya harus segera dikoreksi. Oleh siapa? Oleh otoritas yang memiliki kewenangan dan kemampuan,” kata Dicky, menunjuk pemerintah dan dinas terkait.
Pesan yang sederhana, membumi dan mudah dipahami, menurut Dicky, adalah sebuah hal yang penting untuk mengurangi stigma pada para pasien Covid-19. Pemerintah mungkin tidak bisa bekerja sendiri. “Mereka bisa menggandeng tokoh masyarakat untuk memberi pemahaman yang benar kepada warga tentang penyakit ini. Termasuk memberi penjelasan bahwa kalau seseorang sudah dinyatakan negatif Covid-19, ya tidak bisa menularkan lagi,” kata dia.
Masalah stigma jika tidak segera diatasi, akan memperburuk penanganan pandemi. “Orang akan menghindar untuk diidentifikasi apakah positif atau negatif. Ini kan berbahaya, bisa meningkatkan penularan” kata Dicky.
Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Maria Ulfah Ansor mengatakan, permasalahan yang terjadi pada Marni atau warga lain yang mengalami perlakuan yang sama dari lingkungannya menunjukkan sosialisasi tentang covid dan penanganannnya kepada masyarakat belum tuntas, sehingga masih terjadi penolakan. “Pemerintah sudah punya protokol. Tinggal diimplementasikan dengan melibatkan pihak yang terkait” kata Maria.
Pemerintah dituntut perlu untuk menyosialisasikan upaya pencegahan covid secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat dan melakukan pendampingan secara komprehensif. Bagi penyintas Covid-19 yang menjadi korban stigma, pasien dan keluarga perlu dilakukan pendampingan secara komprehensif.
Khusus mengenai Marni, menurut Maria, adalah tanggung jawab pemerintah setempat. “Yang bertanggung jawab untuk pemulihan terhadap Wa Ode Marni sebagai pasien Covid dan keluarga adalah tim Gugus Tugas Baubau bersama Dinas Kesehatan melalui RSUD setempat” tegas Maria.
Laporan : Riza Salman